Supriono, seorang pemulung, membawa mayat anaknya menyusuri jalan-jalan di Jakarta karena tidak mampu membiayai penguburannya. Ironis, di tengah masyarakat Ibu Kota yang gemerlap (Tempo Edisi No. 16/XXXIV).
Inilah nasib orang miskin di Ibu Kota. Mencari peraduan hidup di Ibu Kota memang butuh ketekunan dan kesabaran yang berlipat ganda. Apalagi modal yang harus dibawa orang miskin, sekuat tenagapun tak cukup mampu untuk menyambung hidup.
Mencari sesuap nasi saja bagi kaum papa di Ibu Kota sudah merasa cukup dan syukur kepada Tuhan. Saban hari, pontang-panting membanting tulang mencari celah kehidupan; barangkali ada sedikit kenikmatan di sana, secuil harapan meneruskan hidup.
Teriakan sang pengamen di sepanjang perjalanan kereta rel listrik (KRL) jurusan Bogor-Jakarta sudah seperti lonceng tiap hari menghentakkan kedermawanan sang kaya. Di pelataran masjid, stasiun, jalanan, dan tempat ramai lainnya selalu penuh pekikan suara keibaan meminta welas kasih.
Ironisnya, kebanyakan para peminta itu anak kecil belum berumur. Ke mana generasi masa depan bangsa akan ditanggung? Paradoksnya pula, mereka (anak-anak kecil pengamen itu) dikuasai oleh jaringan “mafioso” pengamen. Setoran wajib dilunasi tiap pulang menjual suara, kalau tidak, cercaan dan pukulan harus kuat ditahan muka. Sungguh kasihan anak terlantar ini. Teringat dalam lintasan pikiran saya sebuah grafiti kaos oblong, “Ibu Kotaku tak sekasih ibu kandungku”.
●●●
Kisah pilu itu kisah sedih di hari Minggu. Anak bungsu Supriono, seorang pemulung, meninggal dunia karena muntaber. Sang anak meningal di sebuah gerobak tua. Penghasilannya yang cuma 10.000 rupiah per hari hanya cukup untuk biaya makan beserta kedua anak kecilnya. Ia tak sanggup membayar pengobatan di puskesmas.
Apa lacur, sehelai kafanpun tak sanggup dibeli. Pikirnya, Kampung Keramat di Bogor tempat bermukim kaum pemulung menjadi terminal akhir tempat mencari pertolongan. Baru sampai di stasiun Tebet hendak mengadu ke Bogor, eh ketemu aparat Polsek Tebet.
Si polisi malah curiga, lalu memutuskan mengirim Khaerunisa, mayat anak kecil itu, ke RSCM untuk diotopsi. Supriono tunduk dan menyerah setelah diinterogasi. Tetapi, di kamar mayat RSCM, dia menolak tegas anaknya diotopsi. Lagi-lagi masalahnya kemelaratan, selain ia kasihan pada mayat putrinya yang tenang itu. Keluar dari RSCM pun, tak ada pelayanan jasa ambulans gratis. Maklum, di Jakarta jasa berarti uang. No free lunch for everyone (baca: for the poor).
Merasa cukup punya uang dari sedekah para pedagang sekitar RSCM, Supriono membawa mayat anaknya ke Sri Suwarni, pemilik runah petak yang pernah disewanya beberapa tahun lalu. Alhasil, Sri bersama tetangganya ikut urun rembug menyumbang keperluan penguburan mayat sang anak itu. Bunga surga itu pun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, diantar orang-orang miskin yang kaya amal.
●●●
Kisah sedih sang pemulung itu tak hanya eka di negeri ini. Beragam (bhinneka) versi realitas kehidupan kaum melarat dan berbilang “nasib” yang bahkan lebih pilu dan menyakitkan hati daripada itu banyak jumlahnya, sebanyak nominal kaum miskin di negeri ini. Yakni, sejumlah penduduk Malaysia atau Filipina, katakanlah, untuk hitungan data statistik kaum “prasejahtera” itu.
Tempo kemarin, belum sembuh luka lara bangsa kita akibat percobaan bunuh diri beberapa siswa sekolah di Tegal, lantaran tak mampu membayar biaya sekolah. Bayaran yang hanya beberapa ribu saja, bagi kita, mungkin tak seberapa. Namun, bagi mereka uang tidak seberapa itu amat berharga semahal kehidupan itu sendiri.
Belum lagi, kita menyaksikan uraian air mata yang membanjiri kita akan malangnya nasib sekeluarga yang dibunuh oleh seorang penanggung hidupnya sendiri. Mengapa? Lagi-lagi karena masalah ekonomi, ekonomi, dan ekonomi yang objek penghasilannya digusur pemerintah setempat.
Di belahan timur Indonesia, saudara sebangsa kita, kekurangan gizi, justru di lokasi di mana lumbung padi berasal. Busung lapar hampir mencekik leher semua anak-anak yang mempunyai masa depan cerah, bagi mereka dan bangsa ini. Ironisnya, sang elite pejabat menyangkal kenyataan ini seraya berseloroh: “Ini sebuah kecelakaan semata!” Seolah hati nurani sudah tak bertepi dalam ruang sukma kehidupan.
Diakui atau tidak, kepekaan sosial kita sebagai sebuah bangsa menjadi amat tumpul. Runcingnya katastrofi yang melanda sebagian bangsa di bumi nusantara ini tak lagi mampu mengasah filantropi sosial sebagai bengkel rehabilitasi sosial. Bahkan, ragam bencana alam dan ribuan nyawa yang meninggal sudah tak sanggup lagi mengetuk kesadaran sanubari sekedar untuk memperbaiki krisis kemanusiaan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara.
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dalam Pasal 34 UUD 1945 bukan sebuah mantra ajaib bagi proses kenegaraan kita. Ia hanya figura indah berbentuk untaian kata yang dipajang di dinding konstitusi. Pemeliharaan atas kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar bukan turun secara otomatis dari langit Ilahi yang agung, itu harus ditegakkan oleh negara dan kita semua.
Sejatinya menjadi sebuah bangsa yang satu atas solidaritas bersama, berarti bertekad menanggung hidup suka maupun duka. Maurice Duverger (1979) menyebutnya sebagai “solidaritas psikologis” yang berlaku transhistorik dalam rentang waktu dulu, sekarang, maupun masa mendatang sebagai sebuah bangsa utuh. Jika solidaritas itu terkoyak dan sudah tumpul untuk diasah kembali, bukankah jawabannya cukup “the end of nation-state” (meminjam ungkapan Kenichi Ohmae, 1995).
Derita, duka lara, dan kepedihan seperti yang dialami Supriono, hanya angin lalu saja bagi warga sekitar, justru di tengah gemerlap hidup yang sarat keglamoran di Ibu Kota. Nihilnya kepedulian sosial merupakan agregat dari akumulasi gaya hidup yang melulu mengejar hasrat kebutuhan hidup.
Hasrat kebutuhan hidup yang terus diburu masyarakat kota untuk menggapai kekayaan, gaya hidup, kemewahan, kekuasaan, dan seksualitas. Ini sesuai dengan etika hedonisme: bahwa segala sesuatu yang membawa kenikmatan dinilai baik. Norma dan tata etika sosial diabaikan dan dianggap tidak perlu. Krisis etika terjadi; pusat gravitasi digantikan oleh ekonomi libido yang oleh Jean Baudrillard disebut dengan fetisme masyarakat modern. Yang disembah hanya citra atas realitas, bukan kedalaman hidup. Ruang sosial menjadi hampa makna.
Di sisi lain, kurang berfungsinya pelayanan publik oleh pejabat negara (pemerintah) untuk warga miskin menunjukkan lemahnya etos disiplin dan krisis egalitarianisme. Makna pelayanan publik (to govern) bagi penyelenggara negara seolah sudah digantikan sebagai “pemaksa yang memerintah”. Maka hal itu menjadi sebentuk hard power yang menghasilkan mentalitas penguasa yang ingin terus dilayani, bukan melayani. Dalam perspektif Gramscian, posisi negara menjadi suprastruktur yang mensubordinasi kaum marjinal.
Pelayanan bagi warga miskin terbatas dan dibatasi. Sebab yang memuluskan segalanya ialah uang. Warga seperti Supriono miskin seutuhnya, tunawisma, tak ber-KTP, sementara pemerintah mensyaratkan pelayanan gratis hanya diberikan setelah punya surat keterangan miskin. Jadilah ia warga miskin yang tak berdaya. Bayangkan, nasib orang miskin memang dilarang segalanya. Entah untuk sakit, sekolah, privilese dan seterusnya. Itulah cermin kepongahan kita semua. Kifaya Indonesia!
sumber:http://taufikh.wordpress.com/2008/10/03/orang-miskin-dilarang-segalanya/
11.20.2009
Orang miskin diLarang Segalanya...
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)



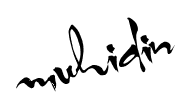
0 komentar:
Posting Komentar